Menyelisik Jejak Cadar dalam Kebudayaan Nusantara
Tulisan ini merupakan pos ulang dari Bincangsyariah.com dengan tambahan gambar
BincangSyariah.Com
– Cadar atau nikab biasa diidentikkan
dengan budaya Arab. Pemakaian cadar kerap dianggap tak sesuai dengan budaya
Nusantara. Pasalnya, pada masa kini pemakaian cadar tampak tidak lazim di
Indonesia. Mengenai hukum bercadar, dalam fikih sendiri terdapat khilafiah.
Bahkan, dalam mazhab Syafii sendiri para ulama berbeda pandangan mengenai
kewajiban bercadar.
Menyelisik Jejak Cadar dalam Kebudayaan Nusantara
oleh Mario Excel Elfando
Jika kita menengok penerapan mazhab Syafii di Hadramaut, Yaman,
dapat kita lihat bahwa di sana hukum bercadar adalah wajib. Sementara itu,
kebanyakan orang Indonesia berkeyakinan bahwa cadar tidaklah wajib. Padahal, terdapat
teori bahwa mazhab Syafii yang dianut mayoritas orang Indonesia dibawa oleh
penyebar Islam dari Hadramaut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dalam
proses penyebaran Islam di Nusantara masyarakat memang tak pernah dikenalkan
dengan cadar? Adakah akulturasi antara cadar dan budaya Nusantara?
Anggapan bahwa cadar tak dikenal dalam khazanah Islam Nusantara rupanya
tidak tepat. Terlepas dari perdebatan mengenai hukum cadar, cadar telah dikenal
di Nusantara dengan nama yang berbeda-beda. Di daerah Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan
Barat, Singapura, dan Sarawak, cadar dikenal dengan nama tudung lingkup;
di Bima dikenal dengan nama rimpu; sedangkan di Kampar, Riau, dikenal
dengan nama maroguok.
Tudung lingkup adalah kain lebar (kain sarung) yang digunakan
perempuan Melayu untuk menutup kepala, muka, dan tubuh bagian atas. Tudung
lingkup memiliki corak dan warna yang variatif. Pada masa lalu perempuan Melayu
harus mengenakan tudung lingkup setiap keluar rumah dan ketika dikunjungi tamu
laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun pada masa kini tudung lingkup sudah
jarang digunakan, tetapi di Jambi masih dipakai dalam festival budaya.
Perempuan Melayu diharuskan bertudung lingkup sejak menginjak usia akil
balig. Cara pemakaian tudung lingkup menunjukkan status dan usia seseorang.
Perempuan yang masih perawan diharuskan menutup rapat wajah serta tubuhnya dan
hanya boleh menampakkan kedua mata. Bagi perempuan yang sudah menikah, tudung
lingkup boleh menutup wajah dan boleh pula tidak, tetapi tetap menutup bagian
atas tubuh. Jika perempuan telah lanjut usia, tudung lingkup dipakai secara
longgar dan tidak lagi menutup wajah.
Keharusan
menutup wajah bagi gadis bersesuaian dengan pandangan mazhab Hanafi yang
mengharuskan perempuan muda menutup wajahnya.
قال الحنفية: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا، لا
لأنه عورة، بل لخوف الفتن
“Menurut
mazhab Hanafi, pada zaman kita kini perempuan muda dilarang mendedahkan wajahnya
di antara laki-laki, bukan karena wajah adalah aurat, melainkan untuk menghindari
fitnah,” (Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz XLI, halaman
134).
Sejak bilakah tudung lingkup dikenal
di alam Melayu? Terdapat beberapa naskah Melayu lama yang dapat menjadi petunjuk
untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, dalam naskah Sulalatus-Salatin
disebutkan,
“Dinihari tadi ia bertemu dengan Hang
Nadim membawa seorang perempuan bertudung, dibawanya naik ke jong Nakhoda
Saiyid Ahmad, dilayarkannya jalan ke Melaka.” (Sulalatus-Salatin, 1612)
Kendati tidak
secara spesifik disebut tudung lingkup, dari naskah tersebut dapat diketahui
bahwa tudung secara umum telah dikenal pada masa Kesultanan Melaka. Boleh jadi
pula tudung sudah dikenal sejak masa pra-Islam. Kebudayaan Sumatra sejak lama
mengenal penutup kepala bagi perempuan, seperti tudung kepala (Batak Karo), tengkuluk
(Jambi), dan tudung manto (Riau). Jenis-jenis penutup kepala ini memang hanya
menutup rambut, tidak menutup leher dan wajah. Namun, hal itu mendorong jilbab
dan cadar lebih mudah diterima oleh masyarakat Melayu.
Kemudian, dalam Tuhfat an-Nahfis disebutkan,
“Syahadan adalah
pada masa kerajaan Yang Dipertuan Muda Raja Ali mengadakan beberapa perkara
yang indah-indah yang mendatangkan nama kerajaan yang elok dan ugama yang
teguh. ... Dan pada masa
kerajaannya berdirilah ugama Islam mendirikan Jumaat dan memerintahkan
orang perempuan bertudung kepala dan menyempurnakan berbuat
masjid yang tiada jadi diperbuat oleh Yang Dipertuan Muda Raja Abd al-Rahman
al-Marhum sebab mangkatnya.” (Tuhfat an-Nafis, 1866).
Penggalan
naskah ini menunjukkan bahwa perempuan Melayu di Kesultanan Lingga diperintahi
untuk bertudung sejak masa pemerintahan Raja Ali bin Raja Ja‘far (1844–1857).
Patut diduga bahwa yang dimaksud tudung dalam naskah ini ialah tudung lingkup.
Hal ini karena tudung lingkup masih dipakai oleh segelintir orang di Pulau
Lingga.
Adapun di Bima tudung lingkup dikenal dengan nama rimpu. Syamsuri
Firdaus, qari asal Bima, dalam diskusi dengan penulis mengatakan bahwa rimpu diperkenalkan
oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro. Mereka adalah dua orang penyebar agama
Islam di Bima. Budaya rimpu makin mengental setelah Sultan Abdul Kahir, raja
pertama Kesultanan Bima (1640), menerima ajaran Islam dan menginstruksikan
kepada kaum wanita untuk menutup aurat dengan sempurna. Pedagang muslim yang datang
ke Bima, terutama wanita Arab dan Melayu, juga mendorong perempuan Bima untuk
mengenakan rimpu. Meski kini banyak orang meninggalkan rimpu, hingga kini masih
ada yang mengenakannya.
Dokumentasi
alif.id
Pemakaian rimpu sama dengan tudung lingkup. Rimpu yang menutup
wajah, sebagai tanda bahwa perempuan yang memakainya belum menikah, disebut rimpu
mpida. Adapun rimpu yang tidak menutup wajah, sebagai tanda bahwa perempuan
telah bersuami, disebut rimpu colo. Rimpu terdiri atas
dua buah kain sarung: satu menutupi bagian bawah tubuh perempuan, sedangkan
satu lagi menutupi kepala dengan cara dililitkan dan dilipat tanpa penyemat.
Sementara itu, di Kabupaten Kampar, Riau, terdapat penutup wajah
yang disebut maroguok. Kata maroguok berasal dari kata berguk
atau burqa’. Berbeda dengan tudung lingkup dan rimpu, maroguok bukanlah
kain sarung yang menyelubungi badan, melainkan kain yang diberi lubang untuk mata
dan terpisah dari kerudung.
Maroguok dibuat karena adanya pandangan binal penjajah Belanda
terhadap perempuan yang tengah bertani dan berkebun. Datuk Engku Mudo Songkal
(1862–1927), seorang ulama dan pendiri Masjid Jami Air Tiris, menyuruh
perempuan memakai maroguok agar terhindar dari pandangan laki-laki yang bukan
mahram. Selain itu, maroguok juga dipakai untuk menghindari sengatan panas
matahari di ladang. Zakaria, ahli waris Datuk Engku Mudo Songkal, dalam
wawancara daring dengan penulis mengatakan, maroguok dapat dipakai oleh
perempuan semua usia. Sayangnya, pemakaian maroguok mulai ditinggalkan sejak
kemerdekaan.
Dengan demikian, pemakaian cadar atau penutup wajah sebenarnya
bukanlah sesuatu yang asing di beberapa daerah Nusantara. Tudung lingkup,
rimpu, dan maroguok menjadi bukti bahwa budaya Nusantara dapat berakulturasi
dan beradaptasi dengan ajaran Islam. Sebagai bagian dari khazanah budaya Islam
Nusantara, sudah sepatutnya cadar khas Nusantara dilestarikan dan dikenalkan
kembali guna mengurangi pendiskreditan masyarakat terhadap perempuan bercadar.



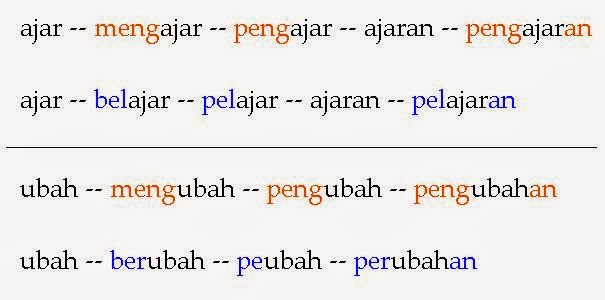

Comments
Post a Comment